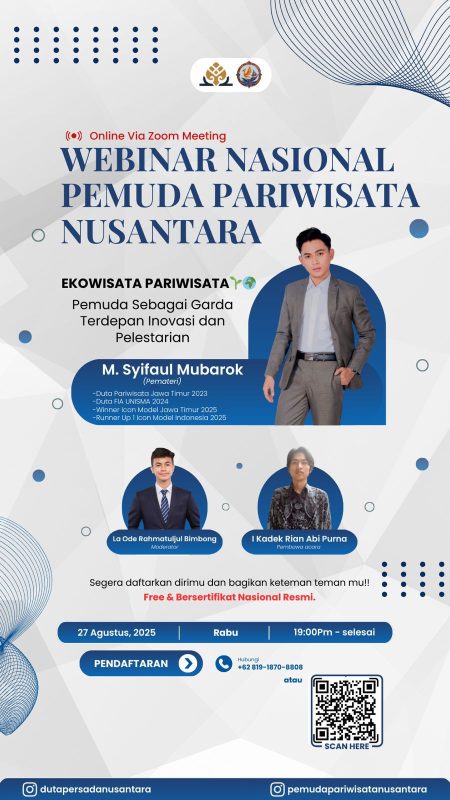Delapan puluh tahun kemerdekaan adalah rentang waktu yang panjang. Dari sebuah negara yang merangkak dari keterpurukan akibat penjajahan, Indonesia kini berdiri sebagai negara berdaulat dengan populasi lebih dari 300 juta jiwa. Selama delapan dekade ini, kita telah melewati berbagai fase: pergolakan politik, pembangunan nasional, reformasi, hingga era digital yang serba cepat. Namun, di tengah segala pencapaian itu, pertanyaan yang menggelitik nurani tetap relevan: apakah kemerdekaan yang diperjuangkan dengan darah dan air mata telah menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat? Pertanyaan ini penting, sebab sejarah dunia membuktikan bahwa kemerdekaan politik tidak selalu otomatis berbanding lurus dengan kemerdekaan ekonomi dan sosial.
Kemerdekaan pada 1945 adalah awal, bukan akhir perjuangan. Bung Karno pernah berkata, “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” Kalimat ini menegaskan bahwa tantangan pascakemerdekaan jauh lebih kompleks. Musuh terbesar bangsa kini bukan lagi kekuatan asing, melainkan ketidakadilan struktural, korupsi yang mengakar, kesenjangan ekonomi, dan rendahnya kesadaran kolektif untuk membangun bangsa. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, masalah-masalah ini adalah hambatan yang menghalangi terwujudnya keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.
Pembangunan ekonomi memang mengalami kemajuan signifikan. Indonesia kini masuk dalam jajaran 20 besar ekonomi dunia (G20) dengan pertumbuhan PDB yang relatif stabil di kisaran 5% per tahun. Infrastruktur seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan transportasi publik modern semakin berkembang. Namun, di balik statistik positif ini, masih ada jutaan rakyat hidup di bawah garis kemiskinan. Data BPS 2024 menunjukkan sekitar 9,4% penduduk masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Angka ini memang menurun dibanding satu dekade lalu, tetapi tidak menutup fakta bahwa kemiskinan bersifat multidimensional—meliputi keterbatasan pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap kesempatan ekonomi.
Kesenjangan sosial tetap menjadi luka lama yang sulit sembuh. Kota-kota besar dipenuhi gedung pencakar langit dan pusat perbelanjaan mewah, tetapi di banyak sudut negeri, anak-anak masih harus berjalan berkilometer untuk sekolah atau bekerja di usia belia demi membantu ekonomi keluarga. Fenomena ini menggambarkan *two-speed development*, di mana sebagian masyarakat melaju pesat sementara yang lain tertinggal jauh. Jika dibiarkan, jurang ini dapat memperburuk ketegangan sosial dan mengikis rasa persatuan.
Persoalan lain adalah pemerataan pembangunan. Pulau Jawa masih menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi, sementara daerah-daerah seperti Papua, Maluku, dan sebagian Nusa Tenggara tertinggal jauh. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua hanya berada di angka 62, jauh di bawah rata-rata nasional 74. Ketimpangan wilayah ini menunjukkan bahwa desentralisasi belum sepenuhnya berhasil mendorong pertumbuhan yang merata. Tanpa strategi afirmatif yang tepat sasaran, daerah tertinggal akan terus menjadi penonton dalam pembangunan nasional.
Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi cermin nyata kualitas kesejahteraan. Walaupun angka melek huruf dan harapan hidup meningkat, kualitas pendidikan di daerah terpencil masih memprihatinkan, dengan kekurangan guru berkualitas dan fasilitas yang minim. Di sektor kesehatan, banyak daerah hanya memiliki layanan dasar di ibu kota kabupaten, sementara desa-desa di sekitarnya harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk mendapatkan perawatan. Hal ini membuktikan bahwa kemerdekaan belum sepenuhnya diartikan sebagai kesetaraan akses layanan publik.
Korupsi adalah momok yang merusak sendi-sendi kesejahteraan. Transparency International pada 2024 menempatkan Indonesia di peringkat 110 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi. Artinya, kebocoran anggaran masih menjadi masalah serius. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, atau bantuan sosial kerap tersedot ke kantong segelintir orang. Selama praktik ini belum diberantas secara sistemik, kesejahteraan akan sulit terwujud meski pertumbuhan ekonomi terlihat baik.
Kedaulatan pangan dan energi juga menjadi tantangan besar. Indonesia masih mengimpor beras, gula, dan bahan bakar dalam jumlah besar. Ketergantungan ini membuat ekonomi rentan terhadap gejolak harga internasional. Padahal, dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, seharusnya kita mampu memenuhi kebutuhan pangan dan energi secara mandiri. Pembangunan sektor pertanian, perikanan, dan energi terbarukan harus menjadi prioritas jika ingin membangun ketahanan nasional.
Meski begitu, bukan berarti kita tidak punya harapan. Generasi muda yang melek teknologi, meningkatnya kesadaran lingkungan, serta tumbuhnya gerakan sosial adalah modal berharga untuk membawa perubahan. Tantangannya adalah mengarahkan potensi ini ke dalam aksi nyata yang berpihak pada rakyat kecil, bukan sekadar tren sesaat. Pendidikan politik yang sehat, kolaborasi lintas sektor, dan pemberdayaan komunitas lokal bisa menjadi penggerak perubahan menuju kesejahteraan yang inklusif.
Pada akhirnya, kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan yang menyejahterakan. Delapan puluh tahun merdeka harus menjadi momentum refleksi: apakah kita puas dengan kemerdekaan politik semata, ataukah kita mau bergerak mewujudkan kemerdekaan yang berwujud nyata dalam kehidupan setiap warga? Pilihan ada di tangan kita semua. Seperti kata Bung Hatta, “Kemerdekaan adalah jembatan emas,” dan tugas kita adalah memastikan jembatan itu mengantarkan seluruh rakyat menuju kehidupan yang adil, makmur, dan bermartabat.
Penulis: Septia Arya Nugraha.
Wasekum Bidang Kewirausahaan Dan Pengembangan Profesi.
Kader HMI Komisariat FKIP Universitas Mataram.